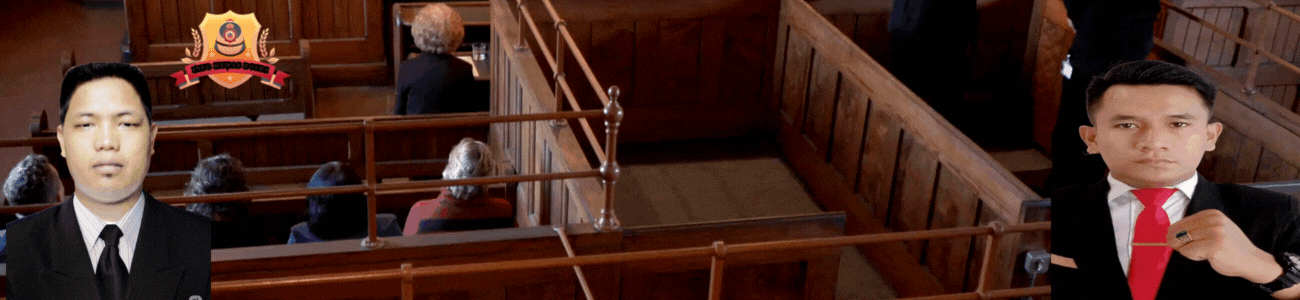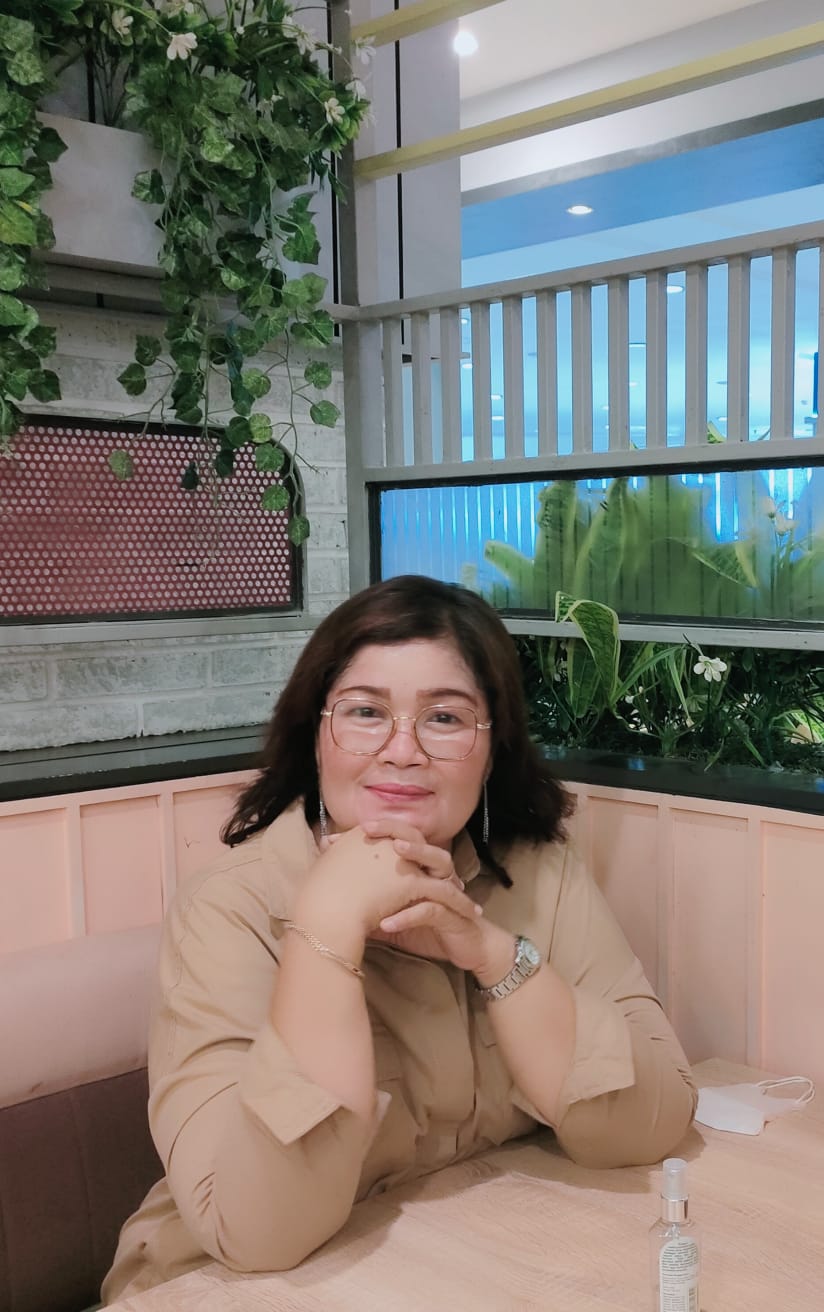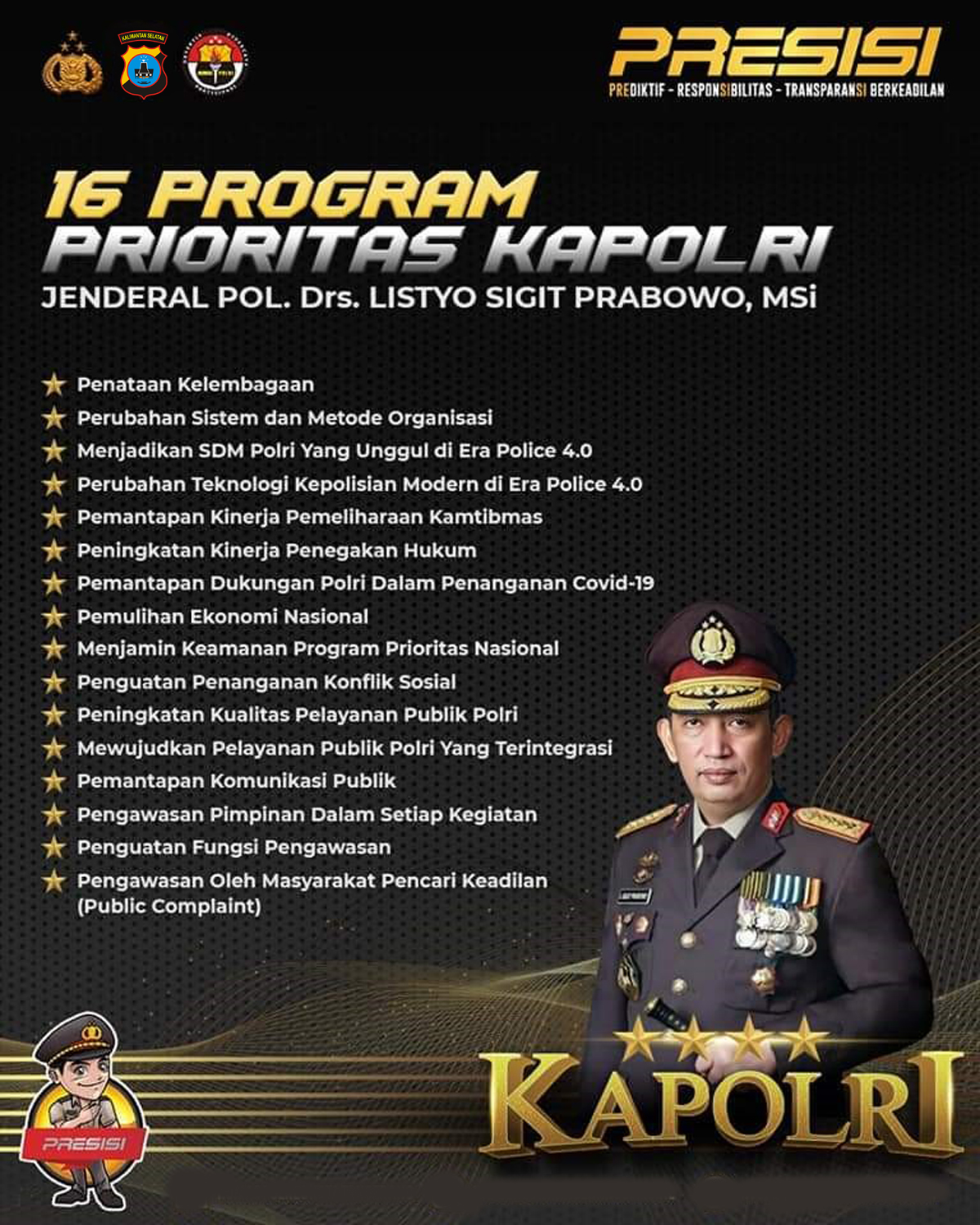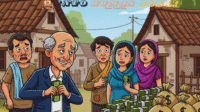Gelombang demonstrasi dengan seruan “Bubarkan DPR RI” yang belakangan merebak bukan sekadar peristiwa spontan. Ia lahir dari akumulasi panjang kekecewaan masyarakat terhadap lembaga legislatif yang dianggap semakin menjauh dari aspirasi rakyat. DPR kerap dipersepsikan minim produktivitas, sarat kepentingan politik, dan tak jarang melahirkan kebijakan kontroversial.
Tidak mengherankan, wacana ekstrem seperti “pembubaran” muncul sebagai simbol kemarahan publik. Namun, pertanyaan mendasarnya: apakah membubarkan DPR benar-benar solusi? Atau justru energi protes ini harus diarahkan menjadi dorongan bagi reformasi kelembagaan yang lebih substansial?
Krisis Kepercayaan terhadap DPR
Survei Indikator Politik Indonesia (2025) mencatat, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya 46%—jauh di bawah TNI maupun Presiden. Sementara itu, catatan KPK menunjukkan puluhan legislator terjerat kasus korupsi sepanjang 2024, mulai dari suap legislasi hingga gratifikasi proyek daerah.
Produktivitas legislatif juga mengecewakan. Dari 256 RUU yang ditargetkan Prolegnas 2020–2024, hanya sekitar 90 yang berhasil disahkan. Ironisnya, undang-undang penting seperti RUU Perampasan Aset justru mandek, sementara aturan kontroversial seperti revisi UU KPK dan Omnibus Law Cipta Kerja melenggang mulus. Fakta ini memperkuat persepsi bahwa DPR lebih berpihak pada elite ekonomi-politik ketimbang rakyat.
Membaca Fenomena “Bubarkan DPR”
Seruan ini bukan berarti rakyat benar-benar ingin meniadakan parlemen. Dalam teori politik, lembaga legislatif adalah pilar demokrasi; tanpa DPR, kekuasaan eksekutif akan absolut. Maka, slogan “Bubarkan DPR” lebih tepat dipahami sebagai ekspresi frustrasi kolektif terhadap praktik oligarki dan politik tertutup.
Fenomena ini sejalan dengan gelombang protes di berbagai negara:
- Thailand (2020): gerakan “Dissolve Parliament” dipicu dominasi militer.
- Hong Kong (2019): protes besar diarahkan pada legislatif yang tunduk pada Beijing.
- Chile (2019): demonstrasi berujung tuntutan perubahan konstitusi.
Polanya sama: saat kepercayaan publik runtuh, parlemen selalu menjadi sasaran.
Reformasi, Bukan Pembubaran
Indonesia tak bisa sekadar menghapus DPR, karena konstitusi menempatkannya sebagai representasi rakyat. Jalan yang realistis adalah reformasi kelembagaan. Beberapa langkah mendesak:
- Transparansi legislasi – Setiap pembahasan RUU wajib terbuka dan disiarkan publik.
- Reformasi pendanaan politik – Mengurangi ketergantungan partai pada sponsor oligarki.
- Mekanisme recall – Penarikan mandat anggota DPR yang korup atau lalai.
- Penguatan etika dan pengawasan – Badan Kehormatan diperkuat dengan auditor independen.
- Pendidikan politik publik – Demonstrasi diarahkan menjadi gerakan advokasi kebijakan jangka panjang.
Pelajaran dari Dunia
Islandia (2009) merespons krisis kepercayaan dengan melibatkan publik dalam perumusan konstitusi baru. Korea Selatan (2016) menghadapi skandal politik dengan transparansi legislatif berbasis digitalisasi. Keduanya membuktikan: krisis legitimasi tidak harus berujung pembubaran, melainkan transformasi institusi.
Penutup
Demo “Bubarkan DPR RI” adalah alarm keras bagi demokrasi Indonesia. Ia mencerminkan jurang kepercayaan yang semakin melebar antara rakyat dan wakilnya. Alih-alih dijadikan alasan untuk meniadakan parlemen, momentum ini seharusnya dimaknai sebagai titik balik reformasi legislatif.
DPR tidak boleh lagi menjadi “menara gading” yang asing dari rakyat, melainkan rumah representasi sejati. Bila sinyal ini gagal dibaca, seruan pembubaran bisa semakin kencang—dan sejarah menunjukkan, ketika rakyat kehilangan kesabaran, reformasi sering hadir dengan cara yang tak lagi bisa dikendalikan.
(Penulis adalah Dosen dan Pengamat Sosial-Politik)